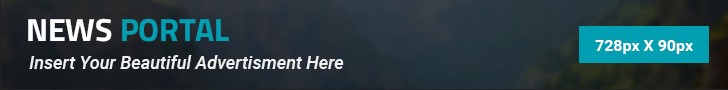Nama Soeharto kembali menggema di ruang publik seiring munculnya wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden ke-2 Republik Indonesia itu. Namun di balik pujian tentang pembangunan ekonomi dan stabilitas politik yang kerap disematkan, tak sedikit yang menilai bahwa Soeharto adalah seorang diktator yang membungkam demokrasi dan menjadikan Indonesia berada di bawah kekuasaan tunggal selama lebih dari tiga dekade.
Era Orde Baru yang dimulai pada 1966 menjadikan Soeharto sebagai figur sentral yang hampir tak tersentuh hukum maupun kritik. Demokrasi dimanipulasi menjadi alat legitimasi, sementara oposisi dibungkam secara sistematis. Partai politik digabung, pers dibatasi, dan kebebasan berekspresi ditekan dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Di bawah slogan “pembangunan,” kekuasaan dijalankan dengan kendali penuh terhadap militer, ekonomi, dan media.
Sistem yang ia bangun bukan sekadar otoriter, tetapi juga represif. Mereka yang dianggap lawan politik kerap dijerat dengan tuduhan subversif, ditangkap tanpa pengadilan, atau dipaksa menghilang. Tragedi Tanjung Priok pada 1984 dan peristiwa Talangsari 1989 menjadi bukti nyata bagaimana kekuasaan dijalankan dengan kekerasan. Ribuan orang menjadi korban, sebagian besar tak pernah mendapatkan keadilan hingga hari ini.
Di sisi lain, Soeharto menciptakan struktur ekonomi yang memperkaya kroni dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kekuasaan yang panjang membentuk lingkaran oligarki yang kuat dan menutup akses rakyat terhadap kesejahteraan yang adil. Sementara itu, rakyat kecil hidup dalam bayang-bayang ketakutan, tidak hanya terhadap aparat negara, tetapi juga terhadap ancaman kehilangan kebebasan berpikir.
Kejatuhannya pada Mei 1998 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Setelah gelombang protes mahasiswa dan rakyat menuntut reformasi, Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Namun meski rezimnya runtuh, jejak otoritariasme yang ia tinggalkan masih terasa hingga kini dalam berbagai bentuk—dari politik yang paternalistik hingga budaya takut mengkritik penguasa.
Wacana untuk menobatkannya sebagai pahlawan nasional kini justru menimbulkan perdebatan moral. Bagaimana mungkin seorang diktator yang memimpin dengan tangan besi, menekan kebebasan, dan terlibat dalam pelanggaran HAM bisa disebut pahlawan? Gelar pahlawan seharusnya menjadi simbol keberanian moral, bukan legitimasi atas kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan rakyat.
Melupakan sisi gelap kekuasaan Soeharto sama dengan menormalisasi kekerasan dan ketidakadilan masa lalu. Sebuah bangsa tidak akan benar-benar maju jika terus menutupi luka sejarah dengan retorika pembangunan. Pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar apakah Soeharto berjasa, tetapi apakah ia pantas dihormati sebagai simbol perjuangan dan kemanusiaan.
Bagi Indonesia, yang kini hidup dalam era demokrasi, mengangkat diktator menjadi pahlawan bukanlah penghormatan terhadap sejarah, melainkan pengkhianatan terhadap ingatan bangsa itu sendiri.